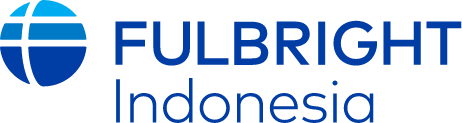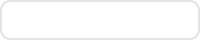Yu Un Oppusunggu. Foto: Istimewa
Yu Un Oppusunggu. Foto: Istimewa
Dua peristiwa penting sejarah bangsa Indonesia terjadi pada tanggal 28 Oktober. Yang pertama, dan lebih terkenal, terjadi pada tahun 1928. Kongres Pemuda II menghasilkan Sumpah Pemuda yang menyatakan bahwa mulai saat itu putra dan putri Indonesia mengaku bertanah-air, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Peristiwa kedua terjadi tepat empat tahun sebelumnya, yakni ketika Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. Dirk Fock, membuka RHS di Balai Sidang Museum van het Koninklijk Bataviaasche Gennootschap van Kunsten en Wetenschappen (Museum Masyarakat Seni dan Ilmu Pengetahuan Kerajaan Batavia), sekarang Museum Nasional atau Museum Gajah.
Tulisan singkat ini mengajak pembaca untuk melihat benang merah antara kedua peristiwa tersebut dalam rangka memperingati dies natalis ke-95 Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Keduanya merupakan serangkaian peristiwa, yang merajut peristiwa-peristiwa lain dalam tonggak sejarah bangsa dan negara Indonesia. Dalam kesatuan tanah-air yang kemudian terwujud dalam konsep negara kepulauan (archipelagic state); kebangsaan Indonesia sebagaimana terwujud sejak Proklamasi; serta kesatuan berbahasa, kiprah institusi dan sivitas akademika FHUI nyata terlihat.
28 Oktober 1924 menjadi fokus kita untuk serangkaian peristiwa kebangsaan. Pada tanggal tersebut, Paul Scholten berpidato di depan Gubernur Jenderal dan para hadirin saat pembukaan RHS. Sambil mempertanggungjawabkan tugas yang ia terima dari Menteri Daerah Jajahan untuk menyiapkan pendirian RHS, guru besar termasyhur dari Universitas Amsterdam ini juga memaparkan secara singkat visinya. Scholten mengatakan bahwa, “[RHS] adalah sebuah sekolah, karena itu harus memuaskan kebutuhan akan pengetahuan, [RHS] adalah sekolah tinggi, karena itu harus mengejar ilmu pengetahuan, [RHS] adalah sekolah tinggi hukum, berhubungan dengan pengetahuan hukum dan pada akhirnya instansi hukum itu sendiri.” Salah satu bentuk perwujudan visi tersebut adalah adanya mata kuliah intergentiel recht (sekarang hukum antartata hukum atau HATAH), yang tidak dikenal dalam kurikulum pendidikan hukum di Eropa.
Mengapa tidak dikenal? Sebab pluralisme masyarakat dan hukum di Nusantara sangat berbeda dengan kondisi masyarakat Eropa. Penduduk Hindia Belanda terbagi ke golongan penduduk (bevolkingsgroep) – Eropa, Timur Asing, dan Bumiputera. Di satu sisi, pembagian demikian berfungsi untuk menopang struktur masyarakat kolonial. Di sisi lain, pembagian tersebut merupakan suatu kondisi yang sulit dielakkan karena kemajemukan masyakat Nusantara. Baik Pemerintah Kolonial maupun para ahli hukum menyadari tantangan ini. Awalnya Pemerintah Kolonial hendak memberlakukan satu hukum – hukum Eropa – bagi semua penduduk. Namun akibat protes Cornelis van Vollenhoven, Pemerintah Eropa menerapkan pluralisme hukum. Bagi golongan Eropa berlaku hukum Eropa; bagi golongan Eropa berlaku sebagian hukum Eropa dan hukum kebiasaan; bagi golongan Bumiputera berlaku hukum adat.
Meski van Vollenhoven membagi Nusantara ke dalam sembilan belas wilayah hukum adat, namun tidak ada yang tahu persis bagaimana bunyi hukum adat tersebut serta jumlahnya. Mengapa demikian? Sebab untuk mengetahui secara persis subtansi hukum tersebut harus terlebih dahulu dilakukan survei atau penelitian. Hukum adat dimiliki oleh masyarakat adat. Sekarang kita menyebutnya sebagai suku bangsa. Namun sebelum Sumpah Pemuda, mereka adalah bangsa. Bagi Belanda, hukum mereka masih merupakan misteri.
Adalah R. D. Kollewijn yang menyakinkan mantan gurunya di Amsterdam tentang kebutuhan akan suatu ilmu yang baru. Dalam suatu percakapan dari Semarang ke pegunungan Dieng, Kollewijn berhasil menyakinkan Scholten bahwa kompleksitas masalah hukum di Hindia Belanda membutuhkan suatu mata kuliah yang sama sekali asing bagi orang Eropa. Intergentiel recht – secara harafiah berarti hukum antarbangsa – menjadi satu dari dua puluh empat mata kuliah dalam kurikulum RHS. Mata kuliah ini terus menjadi bagian kurikulum pendidikan hukum di FHUI sampai sekarang.
“Antarbangsa” di sini berbeda dengan “internasional”. Hal tersebut pertama-tama karena kelompok manusia yang hidup di Nusantara belum dapat dikategorikan sebagai “bangsa” dalam perspektif hukum internasional masa itu. Namun mereka merupakan “bangsa” dalam perspektif antropologi, sebab mereka mempunyai adat-kebiasaan serta hukum yang berbeda dari kelompok manusia lainnya. Itulah sebabnya pemahaman tentang mereka membutuhkan pendekatan keilmuan yang berbeda. Itu juga sebabnya mengapa para peserta menyebut diri mereka dengan nama seperti Jong Java, Jong Soematra, Jong Bataksbond, atau Pemoeda Kaoem Betawi.
Para pemuda kemudian menurunkan derajat bangsa-bangsa menjadi suku-suku bangsa sebagai jalan bagi lahirnya bangsa Indonesia. Kongres ini diketuai oleh Sugondo Djojopuspito, mahasiswa RHS. Tokoh-tokoh lain dalam kongres tersebut juga mahasiswa RHS – Mohammad Yamin, Amir Sjarifoeddin, dan Soediman Kartohadiprodjo.
Yamin adalah tokoh di balik ikrar “satu tanah-air, satu bangsa, satu Bahasa.” Di masa studinya, bersama dengan mahasiswa lain Yamin kerap berdiskusi tentang kebangsaan Indonesia. Diskusi tersebut dapat terjadi di rumah guru besar. Salah satunya di Jl. Pegangsaan No. 56, kediaman Prof. F. M. Baron van Asbeck, yang mengajar hukum internasional. Bersama Amir Sjarifoeddin, ia juga aktif dalam merintis jalan bagi bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Keduanya aktif dalam Kongres Bahasa Indonesia I pada tahun 1938. Ketika itu mereka sudah dua tahun meraih gelar meester in de rechten (Mr.) dari RHS. Nama lain yang terlibat aktif dalam kongres tersebut adalah St. Takdir Alisjahbana.
Alisjahbana terkenal sebagai sastrawan dan linguis. Bersama Amir Hamzah dan Armin Pane, ia mendirikan Poejangga Baroe pada tahun 1933. Latar belakang pendidikan formil mereka adalah ilmu hukum, namun kemudian mereka memilih untuk mengembangkan sastra dan bahasa Indonesia. Alisjahbana juga menjadi salah satu tokoh utama dalam penyusunan dan penerbitan Kamoes Istilah I Asing-Indonesia pada tahun 1945.
Kamus ini sangat penting untuk Indonesianisasi istilah-istilah asing (baca: bahasa Belanda) yang dibutuhkan bukan hanya untuk perkembangan bahasa Indonesia namun juga pendidikan formil, karena dalam masa penjajahan proses belajar-mengajar dilakukan sepenuhnya dalam bahasa Belanda. Tanpa kehadiran kamus ini, maka bahasa Indonesia akan sulit berkembang menjadi bahasa pendidikan formil. Di sisi lain, hanya segelintir bangsa Indonesia yang mampu berbahasa Belanda. Dengan demikian, tanpa ada istilah-istilah dalam bahasa Indonesia ilmu pengetahuan akan sulit berkembang dan aksesnya akan sangat terbatas.
Untuk perkembangan peradaban, berbahasa harus mempunyai pedoman. Sebelum Ejaan Bahasa Indonesia dan Ejaan yang Disempurnakan berlaku, kita mengenal Ejaan Republik. Karena ditetapkan pada 17 Maret 1947 oleh Menteri Pengajaran Suwandi, maka ejaan ini juga disebut sebagai Ejaan Suwandi. Suwandi adalah salah satu pengajar sekaligus ketua Divisi Hukum dari Fakultas Hukum dan Sastra Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia. BPTRI merupakan institusi pendidikan tinggi pertama yang berdiri pasca Proklamasi. Dosen yang mengajar antara lain Djokosoetono, Supomo, Todung Sutan Gunung Mulia, dan Soediman Kartohadiprodjo.
Seiring dengan pemindahan ibu kota Republik, Soediman Kartohadiprodjo mengambil alih kepemimpinan BPTRI dan pengajaran sebab sebagian besar dosen ikut pindah ke Yogyakarta. Soediman menolak untuk bergabung sebagai dosen di Universitas Darurat yang didirikan oleh Pemerintah Belanda. Oleh sebab itu, ia selalu dalam pemantauan polisi intelejen. Perkuliahan dilakukan secara bergerilya dan nomanden. Hal tersebut dilakukan bukan saja karena adanya pemantauan oleh pihak Belanda, namun juga karena tidak ada fasilitas gedung yang tersedia. Untuk menyiasati penyadapan oleh pihak Belanda dan bentuk nasionalisme, perkuliahan berjalan dalam bahasa Indonesia.
Mahasiswa yang “berkuliah” di BPTRI adalah mereka yang secara sadar menolak untuk belajar di BPTRI atas dasar nasionalisme. Di antara mereka terdapat nama Mochtar Kusuma-Atmadja dan Priyatna Abdurrasyid. Nama pertama kemudian terkenal sebagai akademisi, pakar hukum internasional, Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri. Di masa jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri, konsep negara kepulauan diakui dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Dengan demikian, Laut Jawa, misalnya, menjadi wilayah perairan nasional Indonesia, bukan laut internasional. Nama kedua kemudian menjadi akademisi dan Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Sebagai akademisi, Priyatna dikenal sebagai Bapak Hukum Udara dan Ruang Angkasa Indonesia karena pemikirannya yang memperjuangkan kedaulatan negara di ruang udara. Pasca bergabungnya BPTRI dan Universiteit van Indonesië – nama baru dari Universitas Darurat – menjadi Universiteit Indonesia, Mochtar dan Priyatna melanjutkan studi di FHUI dan meraih gelar Mr.
Dilihat dari sisi formil FHUI bukanlah merupakan kesinambungan dari RHS, karena keduanya berdiri dengan dasar hukum yang berbeda. Namun dilihat dari segi kurikulum, FHUI awalnya hanya melanjutkan kurikulum yang diberlakukan di RHS. Dari segi ide, FHUI meneruskan ide Pemerintah Kolonial sebelum tahun 1942 untuk mendirikan suatu universitas dan menjadikan RHS sebagai fakultas hukumnya. Secara sivitas akademika, dosen FHUI merupakan mantan dosen atau mahasiswa RHS. Mereka antara lain adalah Supomo, Djokosoetono, Soediman Kartohadiprodjo, G. J. Resink, W. L. G. Lemaire, Hazairin, Suwandi, dan Subekti. Mengingat fakta yang demikian.
Di luar pemaparan di atas, sivitas akademika juga berkarya di banyak profesi lain bagi Indonesia. Di bidang penegakan hukum terdapat nama Kusuma Atmadja (Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia), Jimly Asshiddiqie (Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia), Soeprapto (Jaksa Agung), dan Yap Thiam Hien (advokat pejuang hak asasi manusia). Di bidang pendidikan, Djokosoetono ikut mendirikan Universitas Gajah Mada, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, dan Sekolah Tinggi Hukum Militer. Iwa Kusumasumantri ikut mendirikan Universitas Padjadjaran, sementara Oeripan Notohamidjojo menjadi rektor pertama Universitas Kristen Satya Wacana. Di bidang pers, terdapat nama R. M. Soemanang (pendiri Kantor Berita Antara), P. K. Ojong (Harian Kompas), dan Sabam Siagian (Jakarta Post). Sebelum dikenal sebagai maestro batik, Iwan Tirta terlebih dahulu menjadi dosen hukum internasional. Di bidang musik, misalnya terdapat nama Solid 80, nama yang menunjukkan solidaritas mahasiswa FHUI terhadap perjuangan demokrasi rakyat Polandia, dan Once Mekel. Di bidang perfilman, ada nama Garin Nugroho. Sebagian alumni lain mendapatkan pengakuan dari negara sebagai pahlawan nasional, antara lain Sukarjo Wirjopranoto, Ide Anak Agung Gde Agung, Sjafruddin Prawiranegara, dan L. N. Palar.
Seperti visi yang dijabarkan oleh Scholten 95 tahun yang lalu, institusi dan sivitas akademika FHUI telah dan terus berkarya untuk memuaskan kebutuhan akan pengetahuan, mengejar ilmu pengetahuan, dan menjawab kebutuhan Indonesia akan hukum dan kebangsaan. Mengamini pernyataan yang dibuat oleh Presiden Kedua Universitas Indonesia pada 5 April 1951, ieder land heft de Universiteit, die het verdient (setiap negeri mempunyai Universitas yang layak baginya): dirgahayu FHUI!
*)Yu Un Oppusunggu adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Last Updated: Apr 1, 2024 @ 1:26 am